Koma
Koma
Oleh : Zahranisa
Perempuan itu
terdiam. Detik yang terus melaju semakin menghakimi, semakin menyudutkanya. Di
sebuah ruangan berukuran tiga kali empat meter. Tubuh di depannya membeku.
Sejuluran selang dari mulut dan dari tangannya. Sayup-sayup suara ‘tut’ ‘tut’
yang keluar dari sebuah mesin di sebelah kepala tubuh di depannya semakin
jelas. Semakin didengar semakin memakinya, seolah meminta pertanggung jawaban
untuk segera dikembalikan di ruangan tidurnya yang tak harus ia bergeming
setiap detik sebagai suar kehidupan. Di genggamnya berkali-kali tangan dingin
itu. Ditatapnya lekat-lekat wajah tanpa ekspresi di depannya.
Berharap sepasang
kelopak mata yang dahulu sering kali berkerling mendengar cerita-cerita
konyolnya itu terbuka kembali. Kembali berkerling. Sekali lagi. Menatap kembali
kornea yang menyiaratkan seribu kebahagiaan, kesedihan atau bahkan kebencian.
Sekali lagi, sungguh! Sekali lagi, untuk memperbaiki retak-retak hubungan yang
telah terjalin tahunan itu sebelum tubuh itu tergeletak di sana. Dia berharap
dari tiap butir udara yang mengawang di ruangan itu. Udara bulan Februari.
Ia pun serba salah
atas keadaan itu. Telah lama mereka berteman. Mengungkap rahasia pribadi di
sudut-sudut malam menjelang tidur. Berbagi musik, cerpen-cerpen, dan ribuan
kisah konyol dari setiap detik mereka bersama. Ledakan tawa, menahan perut dari
kegilaan masing-masing atau menertawakan hal nihil bagi orang lain. Tapi bagi
mereka itu berarti.
Bisakah ini
diperbaiki? Pikirnya dengan terus membisikkan maaf pada wajah ayu di depannya. Tangan
yang sedari tadi digenggamnya semakin membeku, seolah tak ingin melihat lagi
terbitnya mentari esok pagi. ‘Jangan sekarang! Beri aku kesempatan untuk
memperbaikinya! Sekali saja. Sekali lagi, bahkan kalaupun hanya satu detik.
Satu detik untuk membenarkan letak kerah bajumu. Untuk bagaimana kamu bisa
kembali menepuk punggungku ketika sedang berkutat di bangku kramat yang sering
kali kau urung duduki. Katamu duduk di bangku itu membuatku tersihir kekuatan
ghaib yang membuat tak ingin beranjak dari tugas-tugas hingga semua terlihat
pantas disebut selesai’.
Perempuan itu
tidak pernah menduga, bahwa kediaman temannya selama ini bermakna sama dengan
yang dia rasakan. Jikalah waktu berulang dia tak ingin bertemu pada lelaki itu.
Atau bahkan hanya tahu namanya saja sungguh urung dia lakukan. Tetapi pilihan
untuk tidak mengenal sahabatnya itu, sungguh itu bukan pilihan yang dia
inginkan. Bagaimana mungkin kau dapat memilih satu di antara bulang dan
matahari. Sementara kau tahu tanpa bulan malammu akan gelap pekat. Siang tanpa
matahari pun tak akan mampu disebut siang. Tak bisa! Aku tak bisa! Perempuan
itu berkali memaki.
“Ra? Mau nggak
anterin aku?”
”Kemana Ga?”
“Emm, balikin buku
ini?” sambil memperlihatkan buku rangkuman cerpen best seller karya anak
negeri.
“Boleh”
Sore itu
sebenarnya Meira ada temu alumni bersama teman-teman SMA nya. Namun menemani
seorang sahabat yang hidup sebatang kara di tanah perantauan ini lebih menjadi
pilihannya.
“Kenalin nih Ra,
Mas Zul dari Padang sekampung sama aku.”
“Meira” katanya
sambil menyalami laki-laki di depannya.
“Zulfahmi”
laki-laki itu merekahkan senyum ramah.
Sudahlah! Lupakan
saja! Perempuan itu terus mengulang kata-kata itu malam terakhir sebelum dia
tahu semua hal yang selama ini tersembunyi layaknya matahari yang terdiam di
balik hujan. Tak ada salahnya pula mengagumi laki-laki sepertinya. Alim, baik,
berparas menawan dan dia juga berteman dengan sahabatnya. Tidak akan salah
jikalah pada akhirnya mereka bersatu kelak. ‘Namun terlalu dini aku mengakui
ini. Apa salahnya aku mengaku pada Mega’ pikirnya. Sudahlah lupakan saja.
Pastilah ini hanya perasaan sementara seperti halnya dia menyukai banyak lelaki
sebelumnya. ‘Cinta bukan emosi sesaat’. Ya dia tahu, tapi perasaan ini.
Bagaimana mungkin
kau terus diam, sementara kebahagiaan itu, binaran mata yang selalu menjadi
hantu tiap malammu terus mengusik. Membuatmu ingin tahu lebih banyak. Bukankah
kau tak pernah pula mengundang perasaan semacam ini untuk tiba-tiba mengambil
sebagian besar isi otakmu. Membawa sebagian hatimu. Membuatmu ingin selalu
bertemu, atau paling tidak cukup melihatnya.
Pagi itu sebuah
ketukan pintu membuatnya terperanjat. Sebuah ajakan lari pagi bersama komunitas
anak Padang kemudian ditolaknya. Meira lebih memilih berkutat dengan tugas-tugas.
Berlari terkejar dateline. Orang itu.
Tiba-tiba dia teringat. Kalau saja dia ikut, pastilah wajah itu akan
dilihatnya. Ah, tapi sudahlah. Mungkin ini hanya perasaan sesaat. Tiba-tiba
terdengar ponselnya berbunyi.
“Halo?”
“Aku Zul, kamu
yakin nggak ikut? Ini udah di tunggu banyak orang.”
“Zul? Mas Zul?”
“Iya, ini aku
disuruh Mega nelpon kamu. Yuk buruan”
Suara itu mendera
hatinya. Membumbungkan harapnya. Entah ini benar atau salah. Senyum itu kembali
muncul, bersama arak-arakan nada suara yang gemanya berulang-ulang dalam
pikiran. Pikiran tiba-tiba terputar, membalik pada detik ketika netranya mampu
menangkap binar bercampur senyum. Indah sekali!
Senja terpancar
dalam balutan saga. Awan seolah tersedot horizon barat. Menawarkan sensasi
kehangatan yang mulai terganti oleh dingin. Dua perempuan tengah menyatu dalam
kuasa alam. Tersuguh dua gelas air putih dingin. Membentuk sebuah lukisan dua
bidadari berlatarkan senja bernuansa kuning gelap.
“Ga? Mas Zul tuh
umurnya berapa?”
“Mas Zul? Dua tiga
tahun. Ada apa Ra?”
“Nggak. Dia mirip
almarhum kakakku. Perawakannya, senyum, rambutnya, semuanya. Aku hanya banyak
teringat Mas Reno melihat Mas Zul.”
“Beda Ra! Mas Reno
kelihatannya lebih tampan, kalo aku lihat di foto-foto keluargamu.”
“Kamu seolah
menghadirkan kembali Mas Reno di hadapanku Ga.”
Saat itu dia tahu
sahabatnya tidak banyak menganggapi ceritanya. Entah dia mulai sadar sesuatu,
atau memang enggan. Bagai kupu yang tersihir, terbangnya tak lagi imbang.
Kepaknya hanya rendah tak ingin menjangkau bunga yang tinggi. Sontak semua
menjadi sedikit berbeda. Sorot mata Mega berbeda, sungguh berbeda sejak detik
itu.
Semua hal itu
mungkin sedikit akan bertahan lebih lama jikalah malam itu dia tidak memutuskan
untuk ikut nimbrung di perkumpulan anak Padang. Sedikit paksaan dari Mega
membuat sihir di kursi kramatnya padam. Entah apa yang tiba-tiba menuntunnya ke
perkumpulan itu. Ketika dia tiba di sana, hangat anak-anak itu menyambutnya.
“Oke sekarang
giliran pasangan Padang yang bernyanyi. Suiitt suiiitttt...!” kata seorang
laki-laki berambut brindil memandu acara.
“Apa-apaan nih?”
“Baiklah kita
sambut, inilah pasangan baru kita. Mega dan Zuuuulllfahmi..........Ayo kalian
duet. Dion akan mengiringi dengan petikan gitar ajaib.”
Apa? Pasangan?
Sontak Meira merasa keramaian dan riuh tepuk tangan itu perlahan sirna dari
telinganya. Detik menyeretnya ke alam asing yang hanya dia sendiri di sana.
Bagaimana dia akan membawa kesadarannya kini. Bagaimana ini? Haruskah dia tetap
di sana sementara pikirannya menyuruhnya untuk segera berhimpun dalam sepi.
Menepi, mencoba meredakan perih.
Sahabat? Benarkah
ini semua? Bukankah seorang sahabat sudah sepantasnya untuk menyadari setiap
inchi perbedaan di antara keduanya. Meski sedikit saja. Apakah benar Mega tidak
pernah menyadari perasaan kagumnya terhadap Mas Zul. Sementara selalulah Mega
yang pertama kali menemukannya jatuh cinta pada orang lain. Dialah yang selalu
pertama kali benar menebak. Dialah yang selama ini dianggap sahabatnya. Terbaik
selama tiga tahun ini. Meira tidak ingin menjauh, namun bagaimana mungkin dia
akan menghadapi kesakitan melihat kenyataan.
‘Bukan salah Mega.
Tentu saja bukan. Lalu kenapa dia harus mengenalkanku padanya. Apa maksud
hatinya. Sungguh dia menantang maut.’
Meja kramatnya tak
mampu lagi menyihirnya untuk tetap duduk diam disana berjam-jam seperti
biasanya. Dia lebih nyaman bercerita dengan bantal dalam keremangan kamar atau
sesekali malam dia mematikan lampu. Dan bairlah tinggal gelap yang ada. Pekat.
Biar Ibu tidak tiba-tiba masuk kamar. Kemudian tahu kalaulah disini sedang ada
banjir air mata. Cukuplah ini menjadi rahasianya. Cukup dia saja. Tidak ada
sahabat, teman dan yang lainnya.
Sudah sekitar dua
bulan dia mencoba menghindar dari Mega ataupun Mas Zul. Telpon, pesan dan yang
lainnya semua dia abaikan. Biarlah dia ingin mereka anggap tak ada. Berhubungan
dengan mereka hanyalah menyeka lukanya dengan air garam. Bagaimana dia harus
berpura-pura dengan kebahagiaan mereka yang sebenarnya sebuah bencana baginya.
Tidak! Dia tidak bisa! Dia bukan aktris atau tokoh sandiwara.
Sore itu Ibunya
mengetuk pintu kamarnya. Seorang perempuan tiba-tiba muncul dari balik tubuh
ibunya. Sosok perempuan yang selama ini dia hindari. Tanpa bisa menghindar,
mereka pun bertemu. Ya, memang tidak mungkin untuk selamanya menghindar. Dia
bermain di sana cukup lama. Hanya basa basi kaku. Layaknya tak bisa semua terus
dibuat-buat seperti ini. Baik Meira dan Mega pun sebenarnya telah mengetahui.
Sangat tahu.
“Oke Ga, kamu tahu
aku. Kamu tahu segala hal tentangku. Lalu kenapa terus kamu memaksa untuk aku
mengenalnya? Aku bosan Ga dengan kepura-puraan ini. Tidakkah kamu tahu, lukanya
sedalam apa Ga.”
“Lalu aku bisa apa
Ra? Coba kamu pikirkan pula posisiku. Selama enam tahun silam aku mengagumi Mas
Zul sebagai kakak kelasku SMP. Sudah sejak lama. Lebih lama sebelum kamu
mengenalnya. Ketika kau bilang dia mirip kakakmu, kuakui memang iya. Tapi aku
tak ingin kamu lebih mengaguminya lagi. Karena aku telah bersamanya. Aku telah
berikat dengannya. Tapi aku tak pernah mampu membahasakannya padamu. Sekarang,
haruskah aku putus dengan Mas Zul, Ra? Haruskah agar kita bisa berteman lagi?
Sungguh maafkan aku Ra, tidak pernah aku bermaksud egois. Aku menyayangimu Ra.
Sahabatku”
Air mata
menggelanggang dalam kamar itu. Tidak mampu terhindarkan. Dan untuk pertama
kalinya selama mereka berteman. Meira mengusir Mega untuk segera pergi. Matanya
menyorotkan kebencian. Seperti tak pernah ada kisah tiga tahunan itu. Tanpa
penerimaan maaf, atau sebatas kesadaran. Tidak sedikitpun! Dibantingnya kamar
pintu kamar itu setelah Mega keluar. Lukanya membuatnya lebih garang daripada
sebatas atom yang meledak. Pintu itu masih saja diketuk dari luar. Terdengar
ucapan maaf berkali-kali. Namun, dia pun tak bisa menahan luka itu. Biarlah
semua menguap saat ini. Kalaulah mereka tak berteman lagi, biarlah saat ini
memperjelas, mempertegas bahwa mereka cukup
hanya sebatas kenal. Itu saja!
“Ra, aku nggak mau
kamu berubah. Aku benci perbedaan semacam ini.”
Terdengar deru
kendaraan bercampur hujan yang cukup deras. Berangsur suara kendaraan itu
lenyap. Berakhirlah semuanya. Butiran-butiran air terus berjatuhan.
Bergelantung di antara genting-genting. Tepantulkan cahayanya oleh lampu
beranda yang menerangi malam yang mulai pekat. Sepasang mata sembab
terkedip-kedip menatap berkas-berkas pantulan sinar dari balik jendela.
“Ra? Ini ada
telpon dari nomornya Mega. Ponselmu di matikan ya?” Ibunya tiba-tiba masuk
kamarnya.
Tak ada tanggapan.
“Matikan saja bu!”
“Kamu ini kenapa?
Sudah biar ibu saja yang mengangkat...
“Wa’alaykumsalam.
Iya. Apa? Bagaimana kronolgisnya? Asmanya kumat?”
“Ada apa Bu?”
“Bentar...”
“Iya terima kasih,
segera saya beritahu Meira.”
“Mega kecelakaan,
dia parah. Asmanya kumat di tengah perjalanan pulang. Dan dia pun oleng
tertabrak truk. Sudahlah apalagi yang kamu tunggu. Dia koma dirumah sakit
sekarang.”
Bergegas malam
itu, saat itu juga. Ketika jarum pendek masih menyempatkan diri duduk di angka
sebelas. Meira di temani Ibunya berhambur ke rumah sakit. Disana telah ada Mas
Zul yang bermuka sayu.
“Orang tuanya baru
bisa kesini besok. Jadwal penerbangan cepat di cuaca seperti ini susah
didapat.”
Baiklah. Meira
adalah satu orang yang merasa paling bersalah atas semua ini. Berkali-kali dia
menyalahkan diri sendiri. Tapi apalah arti penyesalan itu. Semua telah terjadi.
Angkara membuatnya lupa banyak hal. Dia tak ingat bahwa asma sahabatnya bisa
kambuh kapan saja. Terlebih ketika itu dingin membalut bumi dengan hujan. Tidak
dia ingat bahwa di tanah itu baginya, nama Meira memiliki makna penting.
Temannya, sahabatnya. Dengan tanpa belas kasihan mengusirnya pulang, memaksanya
masuk dalam kubangan hujan.
***
Tangan yang
digenggamnya itu semakin dingin. Wajahnya masih saja ayu meskipun pucat pasi.
Kelopak mata masih saja menutup dan tak urung terbuka barang sekali saja. Haruskah
kesadaran itu terbayarkan dengan darah dan koma semacam ini?
Udara Februari
terasa dingin, terbang menusuk tulang. Menari di antara jiwa-jiwa yang
terhempas dari raganya. Suar kehidupan masih terdengar. ‘tut’ ‘tut’! Ada
kegamangan kalaulah itu tiba-tiba terhenti dan bersiul panjang. Jangan
sekarang.
End
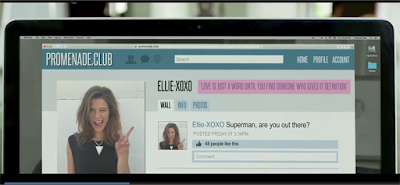
Komentar
Posting Komentar